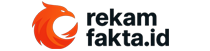www.rekamfakta.id – Keputusan Presiden terkait pemberian amnesti dan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong dan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memicu perdebatan yang sengit di kalangan pakar hukum. Banyak pihak, termasuk akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menganggap langkah ini meragukan, terutama mengingat keduanya merupakan terpidana kasus korupsi dengan putusan hukum yang sudah tetap.
Amnesti dilihat sebagai hak prerogatif presiden yang seharusnya berorientasi pada kepentingan nasional, bukan pada motif politik sesaat. Menurut Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dosen Hukum UGM, penggunaan amnesti dan abolisi harus diartikan sebagai langkah yang lebih strategis, bukannya sekadar tindakan legislatif yang reaktif terhadap situasi tertentu.
Menariknya, amnesti dan abolisi seharusnya muncul dari keinginan untuk memastikan rekonsiliasi yang lebih besar, bukan dari kepentingan pihak tertentu. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana langkah-langkah hukum dapat membawa dampak yang lebih jauh bagi masyarakat.
Menggali Urgensi Rekonsiliasi dalam Kasus Terkait Amnesti
Dalam analisisnya, Dr. Zainal mempertanyakan urgensi rekonsiliasi yang mengitari kasus Tom Lembong. Ia menekankan bahwa jika proses hukum berjalan dengan baik, intervensi semacam itu menjadi tidak perlu. Kecurigaan yang ada adalah keputusan ini tidak lain didasari oleh kepentingan politik semata.
Lebih jauh, Dr. Zainal mengajukan pertanyaan kunci: “Apa yang perlu direkonsiliasi?” Dalam situasi seperti ini, analisis yang lebih dalam tentang relasi kekuasaan menjadi sangat penting. Komunikasi politik yang baik seharusnya mengedepankan keadilan dan transparansi.
Salah satu kekhawatiran utama adalah adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan. Jika amnesti diberikan tanpa dasar yang kuat, hal ini bisa menciptakan preseden buruk. Kebijakan yang muncul akan lebih berdasarkan motivasi politik ketimbang kepentingan publik yang lebih luas.
Persepsi Publik Terhadap Keputusan Amnesti dan Abolisi
Respon masyarakat terhadap keputusan ini juga sangat beragam. Banyak yang merasa bahwa langkah tersebut menunjukkan ketidakadilan dalam sistem hukum di Indonesia. Pada saat yang sama, mereka mempertanyakan efek jangka panjang dari kebijakan ini terhadap citra pemerintah.
Dalam konteks ini, Zaenur Rohman, seorang peneliti di Pusat Kajian Anti-Korupsi (PUKAT) UGM, memberikan pandangan yang bernada sama. Ia menegaskan bahwa amnesti seharusnya merupakan alat yang dipergunakan dengan sangat hati-hati, dalam konteks hukum yang layak. Jika tidak, fungsi sebenarnya bisa terdistorsi.
Zaenur menegaskan pentingnya melihat kasus-kasus lain yang juga mengalami ambiguitas hukum. Ia menyebutkan bahwa banyak orang menjadi korban dari permainan politik yang terjadi dalam konteks hukum, yang tidak jarang mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.
Menegakkan Transparansi dalam Proses Hukum di Indonesia
Melihat fakta di lapangan, diperlukan langkah-langkah lebih transparan dari pemerintah. Dalam hal ini, penerimaan kesalahan pada prosedur hukum menjadi aspek vital yang tidak dapat diabaikan. Jangan hanya memanfaatkan pengampunan sebagai solusi jangka pendek.
Zaenur juga mengingatkan bahwa, jika ada kesalahan prosedur yang nyata, seharusnya hal tersebut diakui dan dibenahi dengan cara yang transparan. Ini akan menjadi langkah yang lebih baik ketimbang hanya memberikan amnesti sebagai jalan keluar.
Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana kewenangan presiden digunakan dalam konteks hukum dan keadilan sosial. Jika tidak, akan muncul lebih banyak kebijakan yang dapat memperburuk keadaan.
Amnesti dan abolisi, seharusnya bukan sekadar peluang yang diberikan secara sembarangan, tetapi haruslah berlandaskan pada argumen hukum yang kuat. Pada akhirnya, upaya penegakan hukum harus selalu mengutamakan kepentingan publik dan keadilan sosial dalam setiap prosesnya.